Pangeran Diponegoro, Seorang Pembelajar di Jalan Perlawanan
 Yogyakarta, jogja-ngangkring.com – Dalam tradisi Islam Nusantara, haul bukan sekadar penanda tanggal wafat seseorang. Haul adalah ruang ingatan kolektif, momentum untuk meneladani laku hidup, nilai, dan jejak pemikiran seorang tokoh yang semasa hidupnya memberi pengaruh bagi umat dan zamannya. Karena itu, Peringatan Haul ke-171 Pangeran Diponegoro tidak berhenti pada doa dan penghormatan, melainkan menjadi ajakan untuk kembali membaca warisan nilai yang ia tinggalkan. Peringatan Haul ke-171 Pangeran Diponegoro bukan sekadar momentum mengenang wafatnya seorang tokoh besar dalam sejarah Jawa dan Nusantara. Lebih dari itu, haul ini mengajak kita menengok kembali dimensi personal Diponegoro sebagai seorang pembelajar—seorang pangeran yang menempuh jalan ilmu dan laku spiritual, sebelum akhirnya menempuh jalan perlawanan.
Yogyakarta, jogja-ngangkring.com – Dalam tradisi Islam Nusantara, haul bukan sekadar penanda tanggal wafat seseorang. Haul adalah ruang ingatan kolektif, momentum untuk meneladani laku hidup, nilai, dan jejak pemikiran seorang tokoh yang semasa hidupnya memberi pengaruh bagi umat dan zamannya. Karena itu, Peringatan Haul ke-171 Pangeran Diponegoro tidak berhenti pada doa dan penghormatan, melainkan menjadi ajakan untuk kembali membaca warisan nilai yang ia tinggalkan. Peringatan Haul ke-171 Pangeran Diponegoro bukan sekadar momentum mengenang wafatnya seorang tokoh besar dalam sejarah Jawa dan Nusantara. Lebih dari itu, haul ini mengajak kita menengok kembali dimensi personal Diponegoro sebagai seorang pembelajar—seorang pangeran yang menempuh jalan ilmu dan laku spiritual, sebelum akhirnya menempuh jalan perlawanan.
Diponegoro terlahir sebagai Raden Mas Mustahar, putra sulung Sultan Hamengkubuwana III. Namun sejak kecil ia tidak dibesarkan dalam lingkungan istana, melainkan diasuh oleh neneknya, Ratu Ageng Tegalrejo. Pilihan pengasuhan ini kelak membentuk jalan hidup Diponegoro secara mendasar. Ia tumbuh di luar tembok keraton, jauh dari intrik kekuasaan dan kemewahan istana, hidup lebih dekat dengan alam, rakyat, serta kehidupan religius. Meski secara status ia adalah pangeran dan memiliki akses penuh terhadap pendidikan keraton serta tradisi adiluhung Jawa, Diponegoro justru memilih jalur pembelajaran alternatif. Di bawah asuhan neneknya, ia akrab dengan kehidupan santri, berguru kepada para ulama, dan menyerap nilai-nilai kesederhanaan, keprihatinan, serta keadilan sosial. Kedekatannya dengan rakyat bukan hasil romantisasi politik, melainkan pengalaman hidup sehari-hari sejak masa kanak-kanak.
Sejak muda, Diponegoro dikenal tekun mendalami ajaran Islam. Ia belajar fikih, tasawuf, dan tradisi keilmuan pesantren. Kedekatannya dengan para kiai dan ulama membentuk pandangan hidupnya tentang keadilan, kepemimpinan, dan tanggung jawab moral seorang pemimpin. Islam bagi Diponegoro bukan sekadar identitas, melainkan sumber etika perlawanan. Perang yang kelak ia pimpin dipahami sebagai jihad dalam pengertian etis: melawan ketidakadilan, penindasan, dan perusakan tatanan moral masyarakat Jawa. Laku spiritual Diponegoro—tirakat dan pengasingan diri—menjadi ruang refleksi dan pembelajaran batin. Dari sanalah lahir keteguhan sikap dan keyakinan bahwa perlawanan bukan ambisi pribadi, melainkan panggilan sejarah.
Sebagai pangeran Jawa yang tumbuh di luar istana, Diponegoro juga merupakan pembelajar budaya. Ia memahami simbol, mitologi, dan kosmologi Jawa dengan sangat mendalam. Ramalan Jayabaya, konsep Ratu Adil, serta pandangan tentang keseimbangan antara alam, manusia, dan kekuasaan menjadi bagian dari kerangka berpikirnya. Pemahaman ini membuat Diponegoro mampu membaca keresahan rakyat Jawa yang merasa tatanan hidupnya dirusak oleh kolonialisme Belanda dan elite lokal yang berkompromi. Budaya Jawa baginya bukan romantisme masa lalu, melainkan sumber legitimasi moral dan politik. Inilah yang membuat perlawanan Diponegoro memperoleh dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat—petani, santri, bangsawan desa, hingga tokoh-tokoh lokal.
Diponegoro juga seorang pembelajar strategi. Tanpa pendidikan militer formal ala Eropa, ia mempelajari medan, psikologi lawan, dan dinamika sosial Jawa. Taktik gerilya yang ia terapkan—memanfaatkan hutan, pegunungan, desa-desa, serta jaringan rakyat—menjadi pelajaran pahit bagi Belanda. Perang Jawa (1825–1830) bukan sekadar perang fisik, tetapi perang pengetahuan lokal melawan mesin kolonial modern. Ia memahami bahwa kekuatan Belanda terletak pada logistik dan senjata, sementara kekuatan rakyat Jawa terletak pada solidaritas, mobilitas, dan penguasaan wilayah. Pengetahuan ini tidak lahir tiba-tiba, melainkan dari proses belajar yang panjang dan reflektif sejak ia hidup di luar pusat kekuasaan.
Dalam sebagian kronik kesultanan yang ditulis atau disunting dalam bayang-bayang kekuasaan kolonial, Diponegoro kerap digambarkan sebagai pembangkang, ekstrem, atau pengacau stabilitas. Narasi ini tidak bisa dilepaskan dari posisi politik penulisnya—elite keraton yang berkompromi dengan Belanda. Di sinilah pentingnya membaca sejarah secara kritis. Babad Diponegoro, yang ditulis dari sudut pandangnya sendiri, menunjukkan wajah lain: seorang pembelajar yang resah melihat ketidakadilan, seorang pangeran yang sejak awal memilih jalan sunyi di luar istana sebelum akhirnya menempuh jalan perang. Ketegangan antara narasi resmi kesultanan pro-Belanda dan suara Diponegoro sendiri mencerminkan konflik pengetahuan dan kepentingan pada zamannya.
Memperingati Haul ke-171 Pangeran Diponegoro berarti merawat ingatan tentang seorang pembelajar sejati. Ia belajar agama untuk menegakkan etika, belajar budaya untuk memahami rakyatnya, dan belajar strategi untuk melawan penindasan. Dalam diri Diponegoro, ilmu pengetahuan, laku spiritual, dan keberanian berpadu menjadi perlawanan yang bermartabat.
Di tengah zaman yang kerap merayakan kekuasaan tanpa kebijaksanaan, sosok Diponegoro mengingatkan kita bahwa perubahan besar hampir selalu berawal dari proses belajar yang mendalam—tentang diri, masyarakat, dan nilai-nilai yang layak diperjuangkan. (Yun)
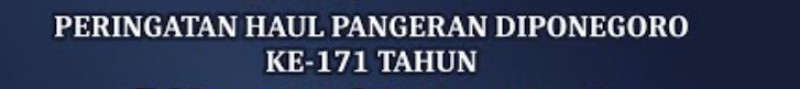




Tinggalkan Komentar
Kirim Komentar